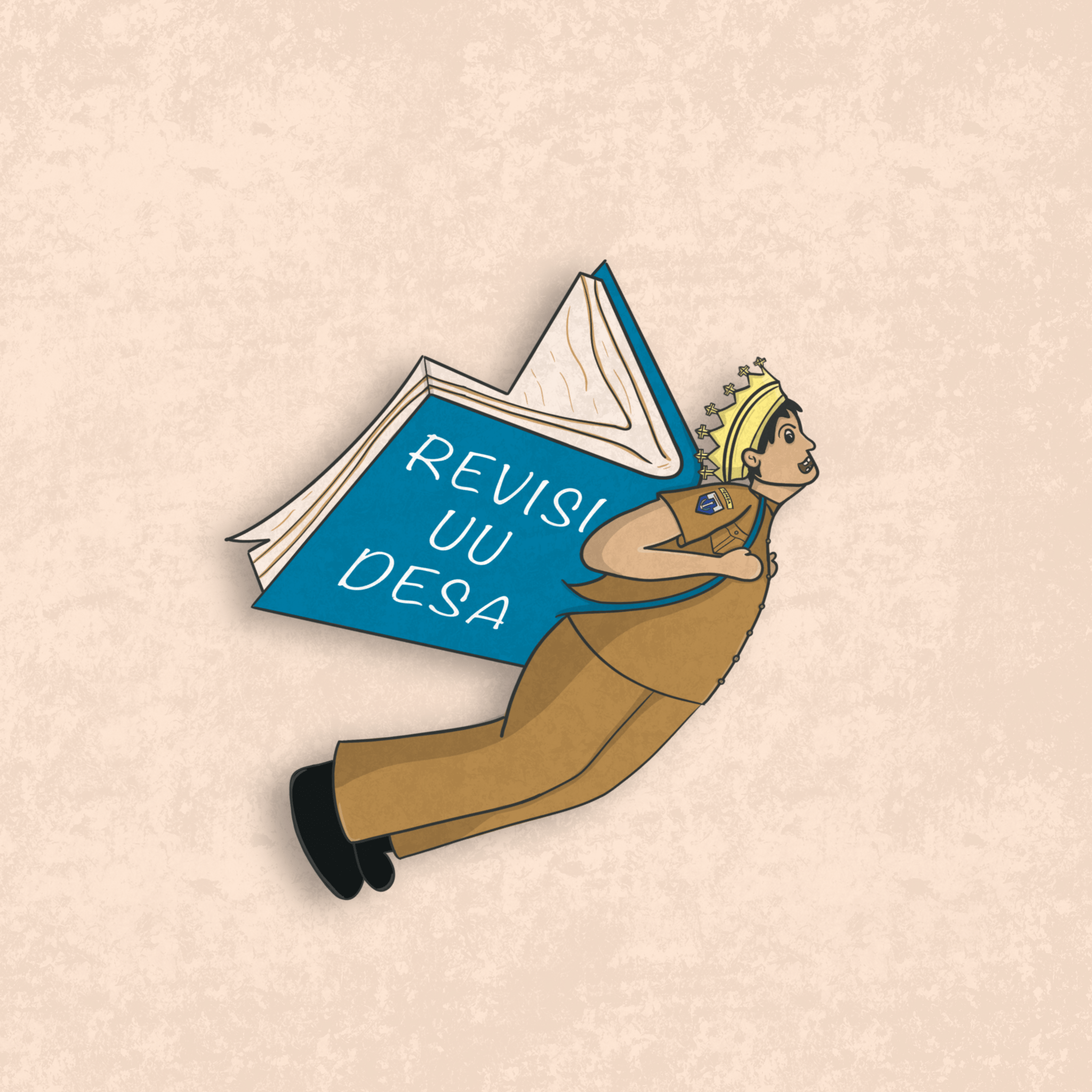Sejumlah massa yang mengatasnamakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Selasa, 6 Februari 2024. Mereka kembali menyuarakan tuntutan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa. Aksi tersebut berlangsung ricuh. Pasalnya, mereka berupaya merusak pagar gedung DPR RI dan melempari aparat polisi dengan batu.
Poin perpanjangan masa jabatan masuk dalam pembahasan revisi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Tuntutan revisi tersebut kemudian disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rapat Panitia Kerja (Panja). Rapat tersebut dipimpin oleh Achmad Baidowi selaku ketua Panja RUU Desa sekaligus Ketua Baleg.
Revisi UU Desa meliputi penambahan beberapa pasal, yaitu Pasal 5A Ayat 3 tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi; Pasal 26 Ayat 2 huruf I; Pasal 50A; dan perubahan frasa kalimat pada Pasal 62 huruf E dan penambahan huruf F dan G. Secara spesifik Pasal 62 huruf G mengatur tentang pemberian tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Selain itu, juga ada penyisipan beberapa pasal, yaitu: Pasal 34A terkait syarat dan jumlah calon kepala desa dalam Pilkades; Ketentuan Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 9 (sembilan) tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut; Rencananya pengesahan RUU Desa terbaru ini akan dilakukan setelah proses Pemilu 2024 berakhir.
Poin perpanjangan masa jabatan merupakan salah satu poin penting yang patut disorot dalam dinamika pembangunan pedesaan. Pasalnya, sengkarut permasalahan politik pedesaan berpotensi menghambat kemajuan desa. Beberapa permasalahan tersebut seperti penyalahgunaan dan politisasi wewenang jabatan, serta praktik politik oligarki hingga korupsi di tingkat desa.
Tuntutan APDESI syarat akan politisasi gerakan massa kepala desa. Beberapa sumber menjelaskan, bahwa tuntutan perpanjangan jabatan ini memiliki hubungan erat dengan agenda politik rezim pemerintahan Jokowi. Mengingat, pada pertengahan tahun 2023 lalu, isu mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode sempat digulirkan.
Namun, usulan tersebut ditolak oleh masyarakat sipil dan beberapa elit politik. Sementara, pada kasus revisi UU Desa, usulan tiga periode masa jabatan kepala desa disepakati oleh sebagian besar fraksi partai politik di parlemen. Pola tuntutan tiga periode perpanjangan masa jabatan tersebut, menandakan adanya kemiripan langkah politik antara APDESI dengan kepentingan Presiden Jokowi.
Selain itu, dinamika perubahan undang-undang desa juga memiliki dimensi politis yang lainnya. Fenomena tarik ulur revisi undang-undang juga dapat dilihat sebagai alat politik transaksional untuk memobilisasi suara di tingkat desa pada Pemilu 2024 lalu.
Indikasi politik transaksional tersebut terlihat dari fenomena massa koalisi yang mengatasnamakan “Kelompok Desa Bersatu”, menyatakan dukungan kepada pasangan calon (Paslon) Prabowo-Gibran. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa Paslon Prabowo-Gibran memiliki kedekatan kepada rezim penguasa Jokowi. Gibran adalah anak sulung dari Presiden Jokowi.
Beragam fakta menunjukkan adanya intervensi Presiden Jokowi dalam kampanye Prabowo-Gibran untuk memenangkan Paslon tersebut. Mulai dari perubahan syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90; pengerahan bantuan sosial oleh menteri-menteri yang merangkap sebagai tim sukses (Timses) Prabowo-Gibran; hingga yang terakhir pemberian gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Hal ini semakin menunjukkan keberpihakan penguasa kepada Prabowo-Gibran.
Perpanjangan Jabatan dan Politik Oligarki
Perpanjangan masa jabatan yang disuarakan APDESI memiliki dalih, bahwa proses pembangunan desa agar bisa lebih maksimal. Sebelumnya, jabatan kepala desa selama enam tahun dan dapat mencalonkan diri hanya dua periode, namun kali ini berbeda. Tuntutan yang diajukan oleh APDESI adalah perpanjangan masa jabatan selama sembilan tahun dan kepala desa dapat mencalonkan kembali sebanyak tiga kali dengan potensi kekuasaan tiga periode, jika meraup kemenangan berturut-turut.
Kondisi perpanjangan masa jabatan memiliki potensi untuk membentuk politik oligarki di tingkat desa. Kurangnya pendidikan politik dan demokrasi di tingkat desa, membuat demokratisasi di tingkat desa tidak sepenuhnya bekerja dengan baik. Fenomena tersebut dikatakan sebagai “pseudo-democracy” atau demokrasi semu.
Secara normatif demokrasi di tingkat desa terwujud, salah satunya dengan adanya pemilihan kepala desa. Namun, pada praktiknya banyak upaya-upaya yang tidak demokratis demi meraih kekuasaan. Praktik politik uang dan korupsi dana desa merupakan sebagian kecil contoh dari cara-cara kotor untuk merebut kekuasaan. Dengan demikian, potensi tumbuhnya oligarki di tingkat desa kemungkinan terjadi.
Jika merujuk pada Richard Robinson dan Vedi Hadiz dalam bukunya yang berjudul “Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets” tahun 2016, kemunculan oligarki itu dimulai dengan adanya ketidaksetaraan ekonomi-politik yang mendalam di antara kelas sosial yang hidup di dalam masyarakat.
Oligarki muncul dari segelintir orang atau kelompok yang memiliki kendali dominan atas sumber daya dan keputusan politik. Penguasaan desa tidak jauh dari sekelompok orang yang memiliki lahan luas atau sebagai tuan tanah. Kondisi tersebut yang membuat mereka sangat mendominasi secara ekonomi terhadap hajat hidup orang-orang biasa di pedesaan.
Tidak sedikit dari para tuan tanah yang turut berpolitik dan ikut serta dalam ajang elektoral di tingkat desa. Sehingga, hanya merekalah yang memiliki latar belakang ekonomi dan politik yang tinggi dapat menjadi penguasa di pedesaan.
Penguasaan desa yang lahir dari sistem demokratisasi yang semu akan memicu konflik kepentingan: baik dalam internal kekuasaan dan eksternal kekuasaan. Fenomena demikian yang membuat kekayaan dan kekuasaan terkonsentrasi dalam sekelompok kecil individu atau kelompok di tingkat lokal, sehingga menyebabkan angka ketimpangan di pedesaan tetap tinggi.
Pseudo-Democracy dan Tingkat Korupsi di Desa
Amanat reformasi yang mendorong demokratisasi di tingkat daerah memiliki sisi lain yang dapat dikritik. Kekuasaan Orde Baru yang sebelumnya sangat tersentral, justru membuat ketimpangan pembangunan dan tersentral di suatu titik saja.
Demokratisasi yang didorong oleh reformasi membentuk desentralisasi politik dan keuangan daerah. Hal demikian yang mendasari pembentukan pemerintah daerah dan juga pemerintah desa. Idealnya, demokratisasi mampu berjalan hingga menyentuh ke tingkat desa. Namun, pada praktiknya, sistem demokrasi politik yang tidak diimbangi dengan pendidikan politik yang baik akan membentuk praktik demokrasi yang semu atau pseudo-democracy.
Praktik demokrasi yang semu, membuat beberapa elit ekonomi di tingkat desa mampu memberikan pengaruh kuat dalam politik. Terlihat, bahwa representasi kepala desa, sebagian besar memiliki latar belakang ekonomi yang tinggi seperti tuan tanah, tokoh dan keturunan keluarga desa, pengusaha besar di desa, dan atribut ideologi kekuasaan lainnya.
Politik desa yang masih tradisional membuat kekuasaan ekonomi dan kultur keturunan keluarga mendominasi praktik perpolitikan di desa. Kondisi ini semakin membuat praktik demokratisasi jauh dari kondisi ideal. Sebaliknya, demokratisasi yang diberikan di tingkat desa justru membentuk oligarki di tingkat desa.
Dengan kondisi politik oligarki desa demikian, praktik penyalahgunaan wewenang kerap ditemukan. Terbukti adanya temuan kasus korupsi di tingkat desa. Data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa korupsi di level desa konsisten menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak atas kasus korupsi oleh aparat penegak hukum sejak 2015 – 2021. Sepanjang tujuh tahun tersebut, tercatat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai total kerugian negara mencapai Rp 433,8 miliar.
Selanjutnya, dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga tahun 2022, terdapat 686 perangkat desa yang terjerat kasus korupsi terkait pengelolaan Dana Desa. Catatan tersebut menunjukkan jumlah kasus yang cukup besar, berdasarkan tingkat kerawanan praktik korupsi di Indonesia. Hal ini yang membuat praktik demokratisasi di tingkat desa tidak memiliki korelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat desa.
Fenomena perpanjangan masa jabatan yang diusulkan oleh APDESI hanya akan memperparah kondisi krisis demokrasi. Cita-cita membangun pemerintahan desa yang bersih semakin jauh panggang dari api. Di sisi lain, praktik politik oligarki di tingkat desa yang semakin kuat hanya akan menghambat proses pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan desa.